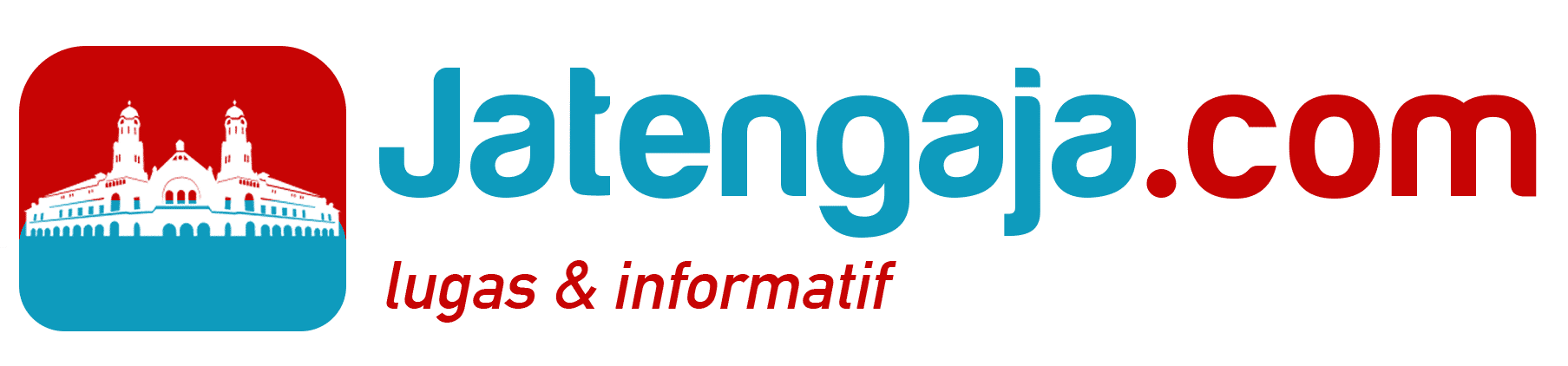Ketika Media Sosial di Indonesia Dijadikan Mesin Disinformasi Demokrasi
Jatengaja.com - Terjadi paradoks peran media sosial dalam demokrasi modern, khususnya dalam konteks aksi demonstrasi. Di satu sisi, media sosial menjadi alat pemberdayaan yang efektif, namun di sisi lain, telah dieksploitasi menjadi mesin disinformasi yang sistematis.
Analisis ini menguraikan bagaimana mekanisme operasi, aktor yang terlibat, dampak destruktif yang ditimbulkan terhadap ruang demokrasi, serta langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk merespons ancaman tersebut.
Seperti yang kita ketahui media sosial telah menjadi infrastruktur penting dalam dinamika demokrasi kontemporer. Platform ini menawarkan ruang tanpa batas untuk deliberasi publik, mobilisasi massa, dan penyebaran informasi.
- Kementan Gelontorkan Dana Rp135 Miliar untuk Hilirisasi Sektor Perkebunan di Jawa Tengah
- Jangan Lewatkan! Investasi SR023T3 & SR023T5 di BRImo, Raih Kupon dan Cashback Berlimpah
- Ahmad Luthfi Dorong Mahasiswa Banyak Hasilkan Karya Inovasi untuk Kemaslatan Masyarakat
- Biografi Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Baru Gantikan Sri Mulyani
- Ratusan Umat Muslim Kota Semarang Ikuti Shalat Gerhana Bulan di MAJT
Hanya saja, karena sifatnya yang terbuka dan algoritmik akhirnya menciptakan kerentanan untuk dimanfaatkan sebagai alat perusak. Anomali terjadi ketika kebebasan informasi justru dimanfaatkan untuk membajak proses demokratis melalui kampanye disinformasi yang terorganisir, terutama dalam momen-momen krusial seperti demonstrasi yang terjadi di berbagai pelosok di Indonesia baru-baru ini.
Sebenarnya, penyebaran disinformasi bukanlah fenomena yang sporadis, melainkan operasi terstruktur yang menyerupai sebuah industri. Di mana di dalamnya terdapat aktor pelaksana dan infrastuktur untuk pabrikasi.
Dalam hal aktor dan infrastruktur, kedua hal ini menjadi alat untuk analisis dalam hal mengidentifikasi dua aktor kunci, pertama siapa koordinator buzzer yang menjadi sutradara yang merancang skenario narasi dan strategi serangan, yang kedua, adalah adanya infrastruktur war room/phone farming, atau bentuk infrastruktur lainnya dengan teknologi tertentu mengoperasikan ribuan akun palsu (bot) dalam mengamplifikasi pesan secara artifisial.
Kolaborasi antara manusia dan teknologi ini akan menciptakan ilusi konsensus (manufacturing consent) dan trending topic yang direkayasa. Kemudian algoritma media sosial didesain untuk membangun engagement yang secara tidak sengaja menjadi amplifier alami bagi konten-konten provokatif bermuatan emosi tinggi (seperti kemarahan dan ketakutan).
Mekanisme tersebut akhirnya akan mempercepat viralitas narasi hoaks yang disebar oleh jaringan buzzer. Lalu, akan terjadi sebuah efek ruang gema atau echo chambers, dimana pengguna yang terkurung dalam gelembung filter menjadi audiens yang paling rentan. Disinformasi yang sesuai dengan bias mereka akan dipercaya dan disebarluaskan tanpa kritik, sehingga kian memperdalam polarisasi.
Dalam kondisi seperti di atas, yang lebih mengkhawatirkan adalah adanya potensi pemanfaatan mesin disinformasi ini oleh aktor yang memiliki sumber daya besar, seperti pihak “penguasa” atau oligarki tertentu, yang berniat untuk mempertahankan hegemoni.
Strategi yang biasa dijalankan adalah melakukan distraksi dan pengalihan isu. Dalam hal ini mereka melakukan pengalihan perhatian publik dari cerita skandal atau krisis dengan membanjiri informasi dengan isu sensasional atau sektarian.
Kemudian melakukan pembunuhan karakter (character assassination) dengan cara menetralisir kritik dan oposisi dengan menghancurkan kredibilitas dan reputasi tokoh-tokohnya melalui kampanye fitnah terkoordinasi.
Pelaku akan terus memonitor dan melakukan aksi intimidasi secara digital dengan memanfaatkan data pengguna untuk memetakan jaringan aktivis dan menciptakan chilling effect melalui taktik doxing atau peretasan.
Kemudian pelaku melakukan aksi monopoli kebenaran dengan cara membanjiri ruang digital dengan narasi tunggal versi “penguasa” sehingga menciptakan realitas alternatif yang sulit dibantah.
Anggaran resmi untuk influencer (seperti yang disorot ICW) hanya merupakan puncak dari gunung es. Operasi yang lebih gelap dengan dana tidak terpantau sebenarnya lebih berpotensi dilakukan dengan skala dan intensitas yang jauh lebih besar.
Efek dari disinformasi yang tersistemasi ini bukanlah main-main. Delegitimasi gerakan sosial yang dilakukan dengan membuat pesan substantif demonstran dapat dikaburkan oleh narasi negatif yang memojokkan.
Kemudian eskalasi kekerasan akan menjadi pusat disinformasi yang dapat memicu ketegangan dan konflik fisik antara massa dan aparat, atau antar kelompok masyarakat.
Inilah yang biasanya akan menjadi polarisasi yang tidak terdamaikan. Masyarakat yang terbelah ke dalam berbagai kubu-kubu tidak lagi mau dan mampu untukdiajak berdialog berdasarkan fakta yang sama.
- Bantuan Dana Hibah Perguruan Tinggi Swasta di Jateng Tahun 2025 Meningkat Capai Rp16,6 Miliar
- Cegah Penyakit Rabies, Dispangtan Solo Sediakan 1.100 Dosen Vaksin Rabies Gratis
- Sosok Inspirarif Idham Chalid, Ketua DPR Termiskin dalam Sejarah di Indonesia
Pada akhirnya hukum dapat digunakan secara instrumental untuk membungkam suara kritis dengan menggunakan konten hoaks sebagai justifikasi, atau tuduhan pidana tertentu.
Dibalik bahaya yang muncul, ada beberapa langkah yang mungkin bisa diambil dan segera dalam menghadapi ancaman tersebut, tentunya dengan adanya pendekatan multi-pihak yang komprehensif.
Beberapa Langkah Antisipasi Pabrikasi Hoaks di Media Sosial
- Literasi digital kritis dengan menjalankan program edukasi yang tidak hanya berfokus pada cara memverifikasi fakta, tetapi juga pada pemahaman tentang ekonomi perhatian, bias algoritma, dan taktik manipulasi buzzer.
- Regulasi yang cerdas dan independen, dimana perlu dilakukan regulasi yang bukan bertujuan untuk membungkam kritik, tetapi untuk menindak tegas pelaku disinformasi terstruktur (organized cyber troops) dan meminta transparansi dari platform. Kemudian dilanjutkan dengan Pembentukan lembaga independen pemantau media sosial yang bisa menjadi opsi.
- Platform media sosial harus di dorong untuk berinvestasi lebih besar dalam deteksi bot, algoritma yang pro-konten sehat, dan kerjasama dengan fact-checker lokal.
- Aparat penegak hukum diharapkan lebih harus proaktif fokus pada aktor intelektual di balik operasi disinformasi, bukan pada pengkritik biasa, ataupun justru membungkam mereka yang kritis dan peduli dengan negeri Indonesia.
Mari kita berharap masyarakat dapat merefleksikan kembali bagaimana bijak bermedia sosial. Dan menghindari anomali yang terjadi dan memperlihatkan betapa instrumen demokrasi dapat dibelokkan untuk agenda anti-demokrasi.
Perlawanan terhadap disinformasi bukanlah perlawanan terhadap kemajuan teknologi, melainkan bagaimana mengupayakan untuk mendidik masyarakat agar lebih kritis, menuntut akuntabilitas platform, menciptakan regulasi yang melindungi ruang publik digital, dan Kembali menfokuskan penggunaan media sosial ke tujuan awalnya diciptakan yaitu mengakomodasi bagaimana ruang komunitas untuk saling berbagi kesamaan untuk tujuan yang lebih positif dan produktif.
Kita tentunya dapat bermimpi, masa depan demokrasi Indonesia nantinya akan sangat bergantung kepada kemampuan kita dalam mengelola anomali kebebasan informasi tersebut. (-)
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Adhitya Noviardi pada 10 Sep 2025